Begini
nasib otak pas-pas-an. Sebenarnya tidak juga, hanya salah jalan dan cenderung
memaksakan. Awalnya memang ada sedikit niat untuk menjalani, tapi lama-lama kok
jadi rodi. Kepala tiap hari migrain, dimana-mana ada rambut rontok, mata rasanya ingin keluar,
bertambah hari badan semakin mengurus saja. Parah.
Kalau
saja dulu Puput lebih mengikuti kata hati, pasti semua tidak akan seperti ini.
Kalau saja dia tidak menempatkan Sarah sebagai rival abadinya, tentu saja ia
tak perlu repot-repot masuk kelas IPA hanya agar tidak dikira kalah saing. Ah
tapi apalah gunanya membicarakan yang sudah-sudah. Tidak menyelesaikan masalah,
hanya akan membubuhkan tanda tanya-tanda tanya di kepala yang tidak pernah
ketemu jawabannya.
UAN,
Ujian Akhir Nasional terhitung sebentar lagi. Hampir dua tahun Puput menjadi
tikus di kelas. Ia selesaikan dua tahunnya dengan niat yang tak pernah bulat. Ia
ikut les ke sana ke mari, pergi ke rumah guru untuk tambahan jam, tapi
hasilnya, ia tetaplah tikus di kelasnya.
Sebenarnya
ia paham materi-materi yang diajarkan, tetapi setiap berhadapan dengan soal,
tangannya bergetar bukan main, keluar keringat dingin, perutnya mules, pingin poop, nafasnya terengah-engah, matanya
seperti sudah copot dan pandangannya menggelap, rasanya dunia adalah neraka
setiap ia berhadapan dengan soal. Kalau sudah seperti itu, beruntung dia masih
bisa mengingat nasihat guru agamanya, beliau bilang Tuhan itu tidak tuli, Ia
bisa mengabulkan semua permintaan orang-orang yang berdoa. Lalu, berdoalah
Puput dengan tangan yang masih gemetaran, bahkan berdoa pun hatinya tetap belum
bisa tenang.
Tahun
pertama ketika ia duduk di kelas dua SMA, nilainya jauh dari segala bentuk
usahanya. Peringkatnya sih nomor dua, tapi dari bawah, dari 28 siswa. Bapaknya
memang demokratis. Ibunya, iya juga sih, tapi suka rewel. Mereka lebih menghargai usaha dan kemajuan Puput. Tapi di
depan Sarah, buku-buku yang biasa jadi bantal tidur ketika kecapekan belajar
sudah beralih fungsi menjadi penutup muka.
Di
tahun keduanya ia mulai berhati-hati, mencoba menjalani dengan hati, tapi tetap
saja terlalu dipaksakan. Sampai suatu ketika, ibu dan bapaknya mengajak ia bicara.
“Wuk, Bapak ndak pernah marah karena
nilai-nilaimu. Buat Bapak, kamu mengerjakan dengan jujur saja itu yang paling
memuaskan—“
“Kalau
Ibu, asal lihat kamu belajar sungguh-sungguh, bangun tengah malam, dan melihat
kamu ada progress, ibu sudah senang.”
“Kamu
kan sebentar lagi mau kuliah, ya biar Bapak sama ibumu yang minta sama Gusti
Allah itu doanya lebih terarah, kamu mau melanjutkan kuliah kemana, dan
mengambil jurusan apa?”
“Harus
dijawab sekarang to?”
“…”
“Saya—“
“Jangan
bilang kamu belum punya gambaran, Wuk.
Walah.. Lha kepriye.” sela ibu.
“Anu..”
“Apa mau jadi bidan? Atau ambil farmasi? Apa mau
kayak mbak Sarah ambil statistik? Ibunya bilang Sarah pingin jadi dokter, tapi
katanya ndak berani nilainya. Kamu ndak usah jadi dokter saja ya. Ibu pikir
selain ndak berani nilainya, juga ndak berani duitnya.”
“Bu.. ndak usah bawa-bawa nama Sarah. Saya kan belum
menjawab, lha kok ibu sudah mirip rel sepur
gitu.”
Selalu
saja seperti itu. Dulu Puput bisa memutuskan untuk masuk ke kelas IPA juga
karena ibunya terus membicarakan Sarah yang notabene selalu mendapat juara satu
di kelasnya, kelas IPA. Sedari kecil ibunya selalu membandingkan Puput dengan
Sarah, sedikit-sedikit Sarah, nilainya mbak Sarah itu lho, peringkatnya mbak
Sarah itu lho, anu-nya mbak Sarah itu lho, itu-nya mbak Sarah itu lho. Parah.
“Saya
mau ke sastra.”
“Sas?”
tanya ibu meyakinkan kalau tidak salah dengar.
“Sastra!”
pertegas Puput sementara bapaknya hanya diam.
“Kamu
ndak lagi panas to, Wuk?”
“Bapak
sama Ibu kan tahu dari kecil saya suka menulis. Apa ada yang aneh dengan
jawaban saya?”
“Umm
ndak, ndak aneh. Tapi dua tahun ini kamu kan jadi anak IPA.” ibu membalas.
“Apa
salah?”
“Tidak.”
“Lalu?”
“Apa
sudah bulat?”
“Ya.”
“Tidak
mau dipertimbangkan lagi? Ikut ke kedinasan, atau kalau pingin ke kedokteran
juga ndak pa-pa, nanti soal biaya gampang. Tapi di farmasi juga oke lho, atau
statistik kayak mbak Sar—”
“Final.”
“Mau
jadi apa nanti?”
“Penulis.”
“Penulis?”
“Iya.”
“Nulis
apa?”
“Apa
saja.”
“Yakin?”
“Seratus
persen.”
“Kita
lagi ngomongin masa depan lhoh.”
“Saya
ndak lagi bicara tentang masa lalu.”
“Kamu
kok sinis?”
“Saya
capek.”
“Kenapa?
Oh mungkin kamu capek karena terlalu memikirkan masa depanmu, gimana caranya
jadi penulis. Iya, kan?”
“Saya
capek mikirin masa lalu.”
“Yang
dipikir masa sekarang saja.”
“Tidak
bisa.”
“Kenapa?”
“Ya
pokoknya tidak bisa.”
“Ya
harus bisa.”
“Pak,
Bu.. sudah ada kalimat buat proposal yang mau diajukan sama Allah untuk masa
depan saya, kan? Yang paling penting doakan saya tidak edan saja.”
“Kok
ngomongnya gitu?”
“Lha
saya sudah stres selama ini.”
“Maksud
kamu?”
“Iya,
masa lalu saya sampai hari ini membuat saya stres.”
“Ibu
ndak paham.”
“Saya
ndak suka dibandingkan.”
“Dibandingkan?”
“Ibu
dan bapak kan selalu mengajari saya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, saya
ndak suka kalah dari mbak Sarah. Saya rela kalah dari siapa saja, kalau
waktunya kalah ya saya kalah. Tapi, tidak untuk Sarah, karena setahu saya, Ibu
selalu membandingkan saya dengan dia.”
“Ibu?”
“Saya
masuk IPA kan karena Ibu rewel. Satu
tahun lalu saya belum bisa mikir realistis. Pelan-pelan saya kubur mimpi jadi
penulis, saya jabat buku-buku Matematika, Fisika, Kimia, Biologi. Tanpa saya
sadari ternyata saya sudah menjadi pembenci, saya tidak benci sama siapa pun
kecuali satu orang saja, mbak Sarah.”
“Ibu
ndak punya maksud seperti itu.”
“Iya,
Ibu ndak ada maksud. Tapi pelan-pelan itu semua membentuk saya menjadi
pembenci. Dan bukan cuma saya yang menjadi pembenci, tapi mbak Sarah juga benci
dengan saya.”
“Darimana
kamu tahu?”
“Sarah
ngomong sendiri sama saya. Dia bilang ibunya membandingkan dia dengan saya.
Sebenarnya saya dengan Sarah itu sama. Dijajah oleh ibu sendiri.”
“Masyaallah—“
“Bu,
mbak Sarah itu dulu teman baik saya. Mulai SMP saya merasa Ibu semakin
menjadi-jadi yang membandingkan, membuat saya terganggu dan merubah diri saya.”
Bapaknya
tutup mulut. Ibunya mulai menangis sehingga membuat Puput merasa bersalah, tapi
ia puas. Tidak pernah ia selega ini, mengutarakan perasaan yang ia bawa ke mana-mana
sedari kecil hingga sebesar ini. Perasaan benci yang membentuknya, membuatnya
salah arah dan tumbuh menjadi anak yang malang.
“Bu,
saya mau menjadi penulis, itu mimpi saya. Yang lalu biarlah menjadi masa lalu.
Tidak ada yang saya sesali, sekarang tugas saya mempertanggungjawabkan apa yang
telah saya pilih lalu fokus di dalamnya. Sekarang saya mulai tahu kenapa saya
tidak pernah mendapat yang terbaik padahal usaha saya sudah mati-matian, doa
saya apalagi. Sekarang saya tahu, Bu. Alasannya sederhana, karena ini semua
bukan untuk diri saya, bukan untuk kebaikan, tapi untuk Sarah. Kalau saya
sedang meratap sama Allah, yang saya bayangkan cuma wajah Sarah. Kelihatannya
saja saya sibuk dengan buku-buku, padahal setiap melihat buku saya ingat
wajahnya dan siap menonjoknya, itu semua membuat saya tidak fokus.
“Saya
tidak mau sampai saya mati membenci Sarah. Saya tidak mau hidup seperti ini.
Saya tidak mau ibu menjadi alasan kenapa saya membenci Sarah. Saya sayang sama
ibu, tapi kalau ibu tidak bisa berubah bahkan sampai saya bisa melampaui Sarah
pun, ibu akan tetap membandingkan. Saya sayang sama ibu. Saya tidak benci, tapi
saya sakit hati.”
Tangisan
ibu semakin menjadi, Puput mendekat dan memeluknya, ia mulai berbisik, “Puput
minta maaf.”
Ceper, Selasa, 26 Maret 2013
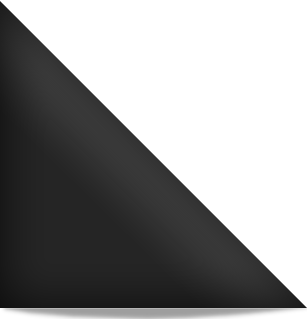
Tidak ada komentar:
Posting Komentar